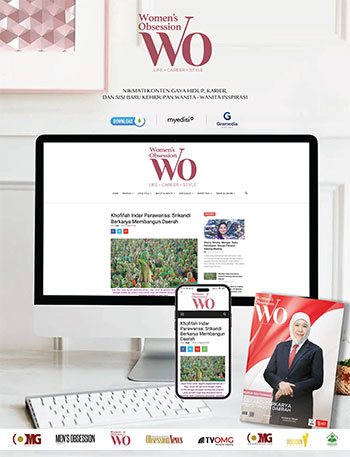Kartini dan Peringatan yang Terlupakan: Sebuah Kritik terhadap Sekularisasi Emansipasi

Oleh: Mutawakkil Abu Ramadhan, Lc
Setiap tahun, tanggal 21 April dirayakan sebagai Hari Kartini. Namun alih-alih menjadi refleksi spiritual atas perjuangan intelektual seorang perempuan Muslim yang hidup dalam kungkungan kolonial, peringatan ini justru lebih sering dibingkai dalam narasi gender sekuler yang dangkal.
Kartini yang dahulu menulis dengan keresahan iman dan kerinduan terhadap cahaya Islam, kini direduksi menjadi simbol emansipasi yang dipisahkan dari nilai-nilai langit.
Padahal, jika kita membaca langsung surat-surat Kartini, terutama setelah ia mengenal Islam dari tafsir dan tulisan para ulama, tampak bahwa jiwanya haus akan keagungan syariat. Dalam salah satu surat kepada Abendanon, Kartini menulis:
“Saya mulai dapat memahami keindahan Islam yang sejati, yang murni… Islam yang tidak diputarbalikkan oleh manusia agar sesuai dengan kehendaknya sendiri.” (Surat kepada Abendanon, 6 November 1902)
Dalam suratnya kepada Ny Van Kol, tanggal 21 Juli 1902, Kartini juga menulis;“Saya bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam, yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah.
Semoga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang Islam sebagai agama disusun dalam surat ke Ny Abendanon, bertanggal 1 Agustus 1903, Kartini menulis;“Ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, yaitu Hamba Allah SWT.
Pernyataan ini bukan sekadar nostalgia spiritual, melainkan kritik tajam terhadap praktik keagamaan yang membungkam perempuan bukan atas dasar wahyu, melainkan karena warisan jahiliyah yang belum tercerabut tuntas.
Kartini bukan pemberontak terhadap agama, melainkan pemberontak terhadap penyimpangan agama yang saat itu direkayasa secara struktural oleh penjajah Belanda.
Dalam surat-suratnya kepada sahabat Belanda-nya, JH Abendanon, Kartini banyak sekali mengulang-ulang kalimat “Dari Gelap Kepada Cahaya” ini. Sayangnya, istilah “Dari Gelap Kepada Cahaya” yang dalam Bahasa Belanda “Door Duisternis Tot Licht” menjadi kehilangan maknanya setelah diterjemahkan Armijn Pane dengan kalimat “Habis Gelap Terbitlah Terang”.
Mr. Abendanon yang mengumpulkan surat-surat Kartini menjadikan kata-kata tersebut sebagai judul dari kumpulan surat Kartini. Tentu saja ia tidak menyadari bahwa kata-kata tersebut sebenarnya dipetik dari Al-Qur’an. Kata “Minazh-Zhulumaati ilan-Nuur“ dalam bahasa Arab tersebut, tidak lain, merupakan inti dari dakwah Islam yang artinya: membawa manusia dari kegelapan (jahiliyyah atau kebodohan) ke tempat yang terang benderang (petunjuk, hidayah atau kebenaran).
R.A. Kartini adalah santri seperguruan dengan Kyai Dahlan (Pendiri Muhammadiyah) dan Kyai Hasyim Asy’ari (Pendiri NU). Ketiga-tiganya adalah asuhan Kyai Sholeh darat, satu dari segelintir ulama yang menentang aturan kolonial saat itu dimana mengajarkan Al Qur'an tidak boleh dengan tafsir dan terjemahan.
Sejak awal, Islam datang sebagai agama pembebas, termasuk membebaskan perempuan dari keterkungkungan sosial. Rasulullah SAW bersabda:
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim,” (HR. Ibnu Majah no. 224).
Imam al-Munawi dalam Faidh al-Qadir menjelaskan bahwa kata “Muslim” di sini mencakup laki-laki dan perempuan, karena hukum taklif bersifat menyeluruh, kecuali ada dalil pengecualian. Maka, siapa pun yang menghalangi perempuan dari menuntut ilmu adalah pelaku tahrif atas semangat Islam itu sendiri.
Ibnul Qayyim rahimahullah pun menggarisbawahi hal ini:
وما كان في الجاهلية من حرمان المرأة من التعليم والرأي فذلك مما جاء الإسلام بإبطاله
"Apa yang terjadi pada masa jahiliah berupa pelarangan terhadap perempuan dalam pendidikan dan pendapat, maka Islam datang untuk membatalkannya." (Tuhfah al-Mawdud)
Ketika Kartini Direbut Narasi Sekuler, Kartini nyaris kehilangan jiwanya. Ia dijadikan ikon kesetaraan gender yang bebas nilai, diseret dalam arus globalisasi ideologi feminisme yang mengukur kemajuan perempuan dari seberapa jauh ia keluar dari rumah, bukan dari seberapa dalam ia mengisi rumah dan dunia dengan ilmu dan iman.
Padahal, emansipasi sejati dalam Islam bukanlah pembebasan dari syariat, melainkan pembebasan dari kezaliman sosial agar syariat bisa diamalkan dengan benar.
Syaikh Muhammad al-Ghazali dalam Tahrir al-Mar’ah fi ‘Asr ar-Risalah menegaskan:
ليس في الإسلام ظلمٌ للمرأة، وإنما الظلم جاء من عاداتٍ جاهليةٍ تسربت إلى المجتمعات، وتُلبس لبوس الإسلام
"Tidak ada kezaliman terhadap perempuan dalam Islam. Kezaliman itu datang dari kebiasaan jahiliah yang menyusup ke dalam masyarakat dan dibungkus seolah-olah bagian dari Islam."
Inilah yang sesungguhnya menjadi keresahan Kartini, sekaligus kegelisahan umat Islam hari ini: ketika agama dipertahankan secara simbolik, namun dirampas maknanya oleh narasi asing dan cecunguk lokalnya yang didaur ulang dalam balutan perayaan nasional.
Kembali ke akar Spiritualitas Kartini, sudah saatnya kita kembalikan Hari Kartini kepada ruh Islam yang mengilhami perjuangannya. Kartini bukan milik feminisme Barat, bukan apa yang ditampilkan oleh Dian Sastrowardoyo dalam film terbaru Kartini. Ia adalah milik umat yang menghargai ilmu, akhlak, dan keadilan dalam bingkai wahyu. Jika emansipasi berarti melampaui batas yang ditetapkan Allah, maka itu bukan kebebasan, melainkan penyimpangan.
Sebagaimana firman Allah:
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin?" (QS. Al-Ma’idah: 50).
Maka, Hari Kartini bukanlah panggung pesta sekulerisasi berkonde dan berkebaya. Ia adalah panggilan untuk kembali membaca jejak iman yang pernah ditorehkan Kartini dalam diamnya yang penuh makna dan kegigihannya meraih ilmu Al Qur'an dari Sang guru, KH. Sholeh Darat.
Dapatkan update muslimobsession.com melalui whatsapp dengan mengikuti channel kami di Obsession Media Group